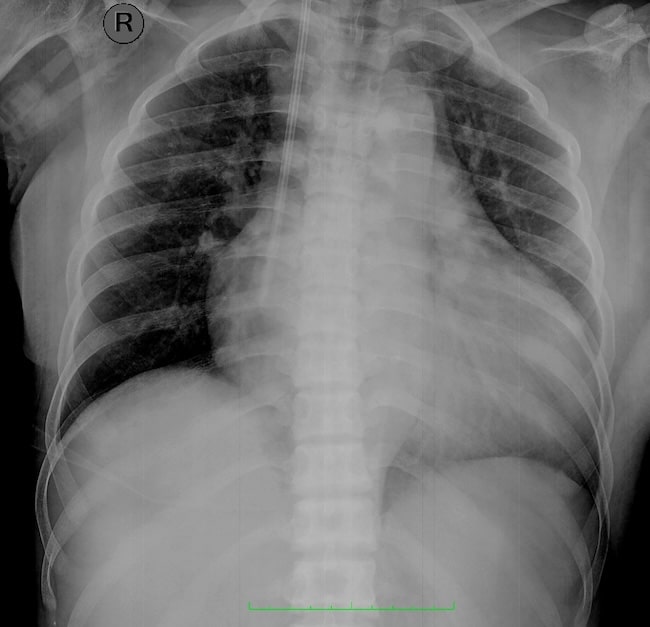Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) mempublikasikan pedoman tata laksana gagal jantung pada tahun 2023. Pedoman ini merupakan pembaruan dari pedoman sebelumnya di tahun 2020. Salah satu pembaruan utama dalam pedoman ini adalah perluasan rekomendasi terkait penggunaan sodium–glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT2i) dalam penatalaksanaan gagal jantung, terlepas dari fraksi ejeksi pasien.
Selain itu, pedoman ini juga membahas mengenai berbagai penyebab kardiak dan non-kardiak dari peningkatan peptida natriuretik, serta bahwa sangat penting untuk mengidentifikasi apakah peningkatan peptida natriuretik benar-benar adalah gagal jantung atau bukan. Pedoman ini juga memberi rekomendasi spesifik untuk pilihan farmakoterapi pada gagal jantung berdasarkan berbagai skenario klinis.[1]
Tabel 1. Tentang Pedoman Klinis Ini
| Penyakit | Gagal Jantung |
| Tipe | Diagnosis dan Penatalaksanaan |
| Yang Merumuskan | Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) |
| Tahun | 2023 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Dokter Sasaran | Dokter Umum, Dokter Layanan Primer, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah |
Penentuan Tingkat Bukti
Penentuan tingkat bukti dalam pedoman klinis ini didasarkan pada telaah literatur terhadap berbagai sumber otoritatif dan dokumen konsensus internasional, termasuk ESC Guidelines 2021, AHA/ACC/HFSA Focused Update 2022, serta Universal Definition and Classification of Heart Failure. Bukti ilmiah yang digunakan mencakup meta-analisis, panduan praktik klinis, serta hasil registri besar seperti ASIAN-HF Registry.
Tingkat bukti dan derajat rekomendasi kemudian diklasifikasikan mengikuti sistem European Society of Cardiology (ESC) 2021. Kelas rekomendasi (Kelas I–III) menunjukkan kekuatan bukti dan konsensus klinis terhadap manfaat atau potensi bahaya suatu intervensi, sementara level bukti (A–C) mencerminkan kualitas data yang mendukung, mulai dari hasil uji klinis terkontrol dan meta-analisis hingga pendapat ahli.
Setiap rekomendasi dalam pedoman ini dinilai secara kritis oleh masing-masing kontributor dan ditinjau kembali oleh tim evidence-based medicine (EBM) untuk memastikan validitas ilmiah serta konsistensi dengan praktik berbasis bukti terkini.[1]
Rekomendasi Utama untuk Diterapkan dalam Praktik Klinis Anda
Pedoman ini membahas mengenai peran N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) dalam diagnosis gagal jantung dan bagaimana penerapan klinisnya perlu memperhatikan kemungkinan etiologi non-kardiak dari kenaikan NT-proBNP. Pedoman ini juga membahas mengenai pendekatan diagnosis dan tata laksana gagal jantung sesuai klasifikasinya dan didasarkan pada bukti-bukti ilmiah lebih baru.[1]
Nilai Batasan NT-proBNP
Pemeriksaan NT-proBNP merupakan salah satu parameter laboratorium yang ditekankan kegunaannya dalam diagnosis gagal jantung. Pada pedoman ini diperjelas nilai batasan NT-proBNP pada kasus gagal jantung akut dan gagal jantung kronis seperti tertera pada tabel 1.
Tabel 1. Nilai Rujukan NT-proBNP pada Kasus Gagal Jantung
| Natriuretic Peptide | ||
| NT-proBNP | BNP | |
| Gagal Jantung Akut | >300 pg/mL | >100 pg/mL |
| Gagal Jantung Kronis | >125 pg/mL | >35 pg/mL |
Namun, interpretasi NT-proBNP harus dilakukan dengan hati-hati terutama jika pasien memiliki berbagai komorbid, dikarenakan NT-proBNP dapat meningkat pada kondisi tertentu, termasuk kondisi non-kardiak.
Tabel 2. Kondisi yang Dapat Meningkatkan Kadar NT-proBNP
| Penyebab Kardiak | Penyebab Ekstrakardiak | ||
| Sindrom Koroner Akut | Penyakit Jantung Kongenital | Usia | Penyakit Paru Obstruktif Kronis |
| Emboli Pulmo | Aritmia Atrial atau Ventrikel | Anemia | Hipertensi pulmonal |
| Miokarditis | Memar Jantung | Stroke iskemik | Penyakit kritis |
| Hipertrofi Ventrikel Kiri | Riwayat kardioversi elektrik atau adanya kejut dari ICD | Perdarahan Subaraknoid | Luka bakar |
| Kardiomiopati hipertrofik atau restriktif | Pasca operasi jantung | Gagal ginjal kronis | Infeksi berat |
| Disfungsi hati terutama Sirosis hati dengan Asites | Sindrom Paraneoplastik | ||
| Penyakit Jantung Katup | Kelainan hormonal berat (tirotoksikosis, ketoasidosis diabetikum). | ||
Diagnosis Gagal Jantung dengan Fraksi Ejeksi Terjaga
Diagnosis adanya gagal jantung dengan fraksi ejeksi terjaga melibatkan pemeriksaan ekokardiografi yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri yang dapat dievaluasi pada saat istirahat atau saat beraktivitas. Adapun kriteria tersebut dijabarkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Tanda Adanya Peningkatan Tekanan Pengisian Ventrikel Kiri
| Tanda Ekokardiografi | Sensitivitas dan Spesifisitas | Catatan Khusus |
| LAVI >32 ml/m2 (Irama Sinus) | Sensitivitas 49%, Spesifisitas 83% | LAVI dapat ter-underestimate pada obesitas |
| LAVI >40 ml/m2 (Atrial Fibrilasi) | ||
| E/e’>9 (istirahat) | Sensitivitas 78%; Spesifisitas 59% | |
| E/e’>13 (istirahat) | Sensitivitas 46%; Spesifisitas 86% | |
| E/e’>15 (beraktivitas) | ||
| TRVMax >2.8 m/s | Nilai prediksi positif 92% | |
| TRVMax >3.4 m/s (beraktivitas) | ||
| RSVP >35 mmHg E/A ≥2 | Digunakan pada usia lanjut, obesitas, hipertensi | |
| Tambahan | ||
| RWT >0.42 | Tidak adanya hipertrofi ventrikel kiri tidak menyingkirkan diagnosis gagal jantung dengan fraksi ejeksi terjaga (HFpEF) | |
| LVMI ≥115 gram/m2 (laki-laki) | ||
| LVMI ≥95 gram/m2 (perempuan) | ||
| LV GLS <16% | Sensitivitas 62%; Spesifisitas 56% | |
Oleh karena itu, pengukuran diastolic stress echocardiography diperlukan untuk melihat adanya peningkatan E/e’ maupun TRVMax saat jantung beraktivitas yang merupakan komponen penting dalam diagnosis gagal jantung dengan fraksi ejeksi terjaga. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan adalah olahraga dengan sepeda atau treadmill.[1]
Tata Laksana Gagal Jantung dengan Fraksi Ejeksi Terjaga
Pendekatan tata laksana gagal jantung dengan fraksi ejeksi terjaga mencakup manajemen faktor komorbid, seperti hipertensi hingga tercapai target tekanan darah optimal. Tata laksana rehabilitasi kardiak dengan olahraga aerobik direkomendasikan untuk meningkatkan kapasitas fungsional disamping pengobatan farmakologis.
Pemberian SGLT2i direkomendasikan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas terkait gagal jantung, tetapi pemberian obat-obatan pilar gagal jantung lain seperti RAAS inhibitor dan spironolactone dapat dipertimbangkan untuk diberikan untuk menurunkan morbiditas kardiovaskular.
Berikut merupakan rekomendasi tata laksana pada pasien dengan gagal jantung dengan fraksi ejeksi terjaga (HFpEF):
- Kontrol tekanan darah merupakan aspek utama dalam pencegahan dan pengendalian gejala HFpEF. Renin–angiotensin–aldosterone system (RAAS) blockers seperti angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACE-I), angiotensin receptor blocker (ARB), atau angiotensin receptor–neprilysin inhibitor (ARNI) direkomendasikan sebagai terapi lini pertama pada pasien hipertensi dengan HFpEF.
Beta-blocker (BB) diberikan terutama pada pasien dengan hipertensi disertai riwayat penyakit arteri koroner, infark miokard, atau atrial fibrilasi dengan respons ventrikel cepat. Namun, penggunaannya harus hati-hati karena dapat memperburuk chronotropic incompetence yang sering ditemukan pada pasien HFpEF.
- Terapi suportif seperti latihan aerobik intensitas sedang (misalnya jalan cepat atau bersepeda 20–60 menit, 3–5 kali per minggu) dan program penurunan berat badan terbukti meningkatkan kapasitas latihan dan kualitas hidup.
Loop diuretic seperti furosemide digunakan untuk mengurangi kongesti dan tekanan pengisian jantung, tetapi harus diberikan dengan hati-hati karena risiko dehidrasi, hipotensi ortostatik, dan cedera ginjal akut, terutama pada pasien lansia dengan hipertrofi ventrikel kiri.
- SGLT2i seperti empagliflozin atau dapagliflozin direkomendasikan untuk mengurangi gejala dan risiko rawat inap, namun kontraindikasi pada diabetes tipe 1 dan ketoasidosis.
Mineralocorticoid receptor antagonist (MRA) seperti spironolactone dapat memperbaiki fungsi diastolik, khususnya pada pasien dengan LVEF ≥45% dan kadar BNP tinggi, tetapi harus dihindari jika eGFR <30 mL/min/1.73m², kreatinin >2,5 mg/dL, atau kalium >5,0 mEq/L.
Angiotensin receptor blocker (ARB) seperti candesartan menurunkan angka rawat inap akibat gagal jantung meskipun tidak mengurangi mortalitas kardiovaskular secara signifikan.
- Sacubitril/valsartan (ARNI) tidak menunjukkan penurunan mortalitas keseluruhan, tetapi bermanfaat pada pasien wanita dengan LVEF ≤57%, menurunkan risiko rawat inap dan kematian kardiovaskular hingga 60%.
- Nitrat dan phosphodiesterase-5 inhibitor (PDE5i) tidak menunjukkan manfaat signifikan terhadap kualitas hidup, toleransi latihan, atau biomarker jantung pada HFpEF.[1]
Tata laksana Gagal Jantung pada Gagal Jantung dengan Fraksi Ejeksi Rendah
Penggunaan loop diuretic pada pedoman ini juga telah ditekankan hanya pada pasien dengan gejala kongesti dan bukan sebagai pengobatan rutin. Jika pada pasien didapatkan anemia defisiensi besi, maka suplementasi besi harus dilakukan. Jika penyebab gagal jantung adalah penyakit jantung koroner, maka revaskularisasi harus dilakukan pada pasien.
Berikut adalah rekomendasi PERKI mengenai pemilihan farmakoterapi pada gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah (HFrEF):
- ACE-I merupakan terapi awal pilihan bagi semua pasien dengan gagal jantung disertai fraksi ejeksi ventrikel kiri (LVEF) <40%, kecuali terdapat kontraindikasi. Kontraindikasi meliputi riwayat angioedema, kadar kalium >5,5 mmol/L, stenosis aorta berat, kehamilan, stenosis arteri renalis bilateral, serta kadar kreatinin >2,5 mg/dL (sebagai kontraindikasi relatif).
- BB direkomendasikan digunakan bersama RAAS blocker, antagonis aldosteron, serta SGLT2. BB ideal dimulai untuk pasien tanpa perubahan kebutuhan diuretik dalam waktu dekat, tidak memerlukan inotrop intravena, dan tidak menunjukkan tanda retensi cairan berat.
- Perhatikan adanya kontraindikasi penggunaan BB. Contoh kontraindikasinya adalah syok kardiogenik dan bradiaritmia simptomatik. Penggunaan BB non-selektif harus berhati-hati pada pasien dengan penyakit arteri perifer berat karena dapat memperburuk gejala iskemik perifer.
- ARNI direkomendasikan sebagai terapi alternatif pada pasien HFrEF yang telah menggunakan ACE-I atau ARB.
- SGLT2i direkomendasikan untuk semua pasien HFrEF, baik dengan maupun tanpa diabetes melitus, karena terbukti meningkatkan luaran klinis dan menurunkan mortalitas serta angka rawat inap akibat gagal jantung.
- ARB direkomendasikan sebagai alternatif bagi pasien HFrEF yang menunjukkan intoleransi terhadap ACE-I atau ARNI.
Loop diuretic direkomendasikan untuk mengatasi kongesti dan mempertahankan status euvolemik pada pasien HFrEF.
Ivabradine direkomendasikan bagi pasien HFrEF dengan irama sinus dan denyut jantung istirahat >70 kali/menit, meskipun sudah mendapatkan dosis maksimal yang dapat ditoleransi dari BB, ACE-I, dan MRA.
- Ivabradine juga direkomendasikan bagi pasien HFrEF dengan irama sinus dan denyut jantung istirahat >70 kali/menit yang tidak dapat menggunakan BB, serta telah menerima ACE-I dan MRA, untuk menurunkan risiko perburukan gagal jantung dan kematian kardiovaskular.[1]
Perbandingan dengan Pedoman Klinis dari Negara Lain
Pedoman PERKI ini sejalan dengan pedoman klinis lain, termasuk yang dipublikasikan oleh European Society of Cardiology (ESC) di tahun yang sama. Pedoman ESC juga meningkatkan rekomendasinya terkait penggunaan obat golongan SGLT2i pada tata laksana gagal jantung, yang mana SGLT2i direkomendasikan tanpa membedakan berdasarkan klasifikasi fraksi ejeksi pasien.
Meski demikian, PERKI belum memberikan pedoman spesifik terkait titrasi farmakoterapi, sedangkan ESC sudah mendukung penggunaan rapid optimisation, yang mana dosis disesuaikan secara cepat dan menggunakan intensitas tinggi sembari memantau tolerabilitas.[2]
Kesimpulan
Pembaruan pedoman tata laksana gagal jantung dipublikasikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) pada tahun 2023. Beberapa perubahan utama yang perlu dicatat dalam pedoman ini adalah:
- Perubahan klasifikasi gagal jantung, yakni kini menggunakan fraksi ejeksi terjaga, penurunan ringan, dan rendah.
- Pada penggunaan N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) dalam diagnosis gagal jantung, pedoman ini merekomendasikan untuk memperhatikan kemungkinan penyebab non-kardiak jika terdapat peningkatan NT-proBNP.
- Perluasan rekomendasi penggunaan sodium–glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT2i) seperti empagliflozin atau dapagliflozin, yang mana kini direkomendasikan pada seluruh pasien gagal jantung tanpa melihat fraksi ejeksi, selama tidak didapatkan kontraindikasi.
Loop diuretic hanya digunakan pada pasien dengan gejala kongesti (tidak secara rutin diperlukan).