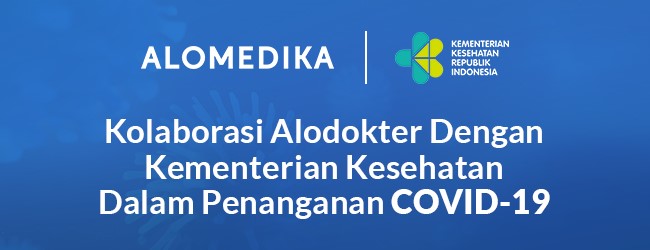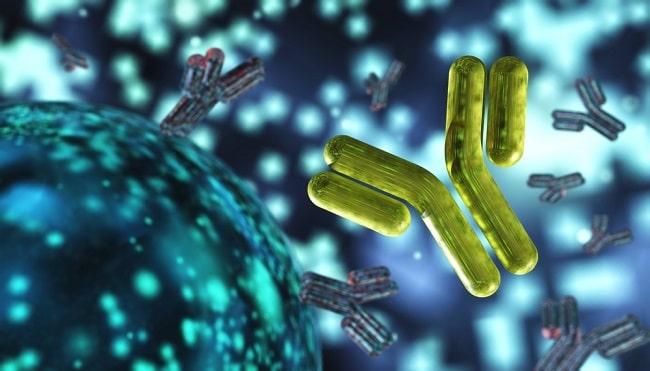Efikasi antibodi monoklonal pada penyakit akibat coronavirus terdahulu membuat terapi ini dipertimbangkan kembali pada COVID-19. Di sisi lain, kemunculan berbagai varian baru pada COVID-19 menimbulkan kekhawatiran tentang efikasi terapi dalam jangka panjang. Terdapat sejumlah studi yang melaporkan bahwa kebanyakan antibodi monoklonal yang pernah menerima otorisasi emergensi untuk pengobatan COVID-19 diketahui tidak efektif terhadap varian atau subvarian baru.[1,2]
Peran Antibodi Monoklonal dalam Pengobatan COVID-19
Peran antibodi monoklonal dalam pengobatan COVID-19 terletak pada kemampuan rejimen ini sebagai imunoterapi langsung dan pasif yang berpotensi mengurangi perkembangan dan keparahan penyakit.
Antibodi monoklonal merupakan suatu terapi antivirus yang dapat menetralisir virus COVID-19 pada pasien yang terinfeksi. Antibodi monoklonal penetralisir terdiri atas protein rekombinan yang berasal dari sel limfosit B dengan molekul yang tersusun atas empat rantai polipeptida dengan dua rantai berat dan ringan yang identik. Ikatan disulfida menghubungkan seluruh rantai polipeptida untuk membentuk tetramer yang menyerupai huruf Y.[3,4]
Mekanisme Kerja Antibodi Monoklonal pada COVID-19
Penemuan antibodi monoklonal yang spesifik dengan afinitas kuat terhadap SARS-CoV-2 dilakukan dengan metode high-throughput screening terhadap sel B dari pasien yang telah sembuh. Afinitas regio Fab (fragment antigen binding) pada struktur antibodi sangat penting dalam mengikat antigen target, sehingga menjadi penentu spesifisitas antibodi.
Dengan spesifisitas dan afinitas yang tinggi, antibodi penetral memiliki cara kerja yang akurat terhadap antigen target sehingga virus dapat langsung dinetralisir oleh komponen sistem imun. Antibodi dapat bekerja dengan cara mencegah ikatan atau fusi virion terhadap sel target (netralisasi) atau melakukan opsonisasi virion atau sel yang telah terinfeksi untuk dihancurkan melalui fagositosis.
Selain itu, mekanisme netralisasi juga dapat terjadi melalui hambatan langsung terhadap masuknya virus, fungsi efektor yang difasilitasi antibodi, dan inaktivasi glikoprotein pendukung masuknya virus. Antibodi monoklonal juga dapat bekerja sebagai suatu agen imunosupresif sehingga mampu membatasi kerusakan yang dimediasi sistem imun dan diharapkan dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas.[5-7]
Antibodi Monoklonal yang Menargetkan Protein S SARS-CoV-2
Beberapa antibodi monoklonal dikembangkan untuk menargetkan protein S pada struktur SARS-CoV-2. Kemiripan urutan asam amino protein S pada SARS-CoV dan SARS-CoV-2 yang mencapai 77% mendorong para peneliti untuk mendayagunakan antibodi monoklonal penetral terhadap protein S pada SARS-COV atau reseptor ACE-2 pejamu.[7]
Perbedaan Efikasi dari Berbagai Jenis Antibodi Monoklonal yang Menargetkan Protein S
Walaupun demikian, penelitian lanjutan mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan kerja antar kandidat antibodi penetral jenis ini.
Sebagai contoh, sejumlah antibodi seperti CR3002 dan F26G19 dapat berinteraksi dengan SARS-CoV dengan cara berikatan terhadap RBD (receptor-binding domain), tetapi pada SARS-CoV-2 antibodi yang sama dapat menargetkan epitop lain selain RBD yang berkompetisi dengan ACE-2 dan mampu menetralisir virus secara lebih poten dibandingkan pada SARS-COV.
Hal ini mengisyaratkan bahwa kemiripan sekuens asam amino pada target protein S dari virus yang berbeda dapat menimbulkan efek klinis antibodi monoklonal pada tingkat yang berbeda.[7]
Casirivimab-Imdevimab
Selain itu, terdapat sejumlah antibodi monoklonal yang dirancang untuk menargetkan beberapa segmen pada struktur protein S SARS-CoV-2 yang telah masuk tahap uji klinis. Salah satu antibodi monoklonal gabungan tersebut adalah kombinasi casirivimab dan imdevimab (REGN-COV2) yang bekerja dengan berikatan dengan epitop berbeda pada RBD protein S SARS-CoV-2 sehingga menghambat ikatan virus dengan reseptor ACE-2.
Dosis yang disarankan untuk masing-masing antibodi monoklonal tersebut adalah 1200 mg dengan cara pemberian intravena untuk pasien dewasa dan anak-anak yang mengalami COVID-19 derajat ringan hingga sedang serta pasien risiko tinggi yang mengalami progresi ke arah COVID-19 derajat berat.[7]
Berdasarkan hasil analisis penelitian fase 2 terkait penggunaan casirivimab-imdevimab, antibodi monoklonal jenis ini tidak disarankan bagi pasien COVID-19 yang dirawat di RS maupun pasien COVID-19 yang memerlukan terapi oksigen atau yang memiliki penyakit komorbid. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa casirivimab-imdevimab hanya menunjukkan manfaat yang terbatas bagi pasien dengan derajat penyakit berat.
Dengan demikian, FDA memberikan otorisasi emergensi penggunaan casirivimab-imdevimab untuk digunakan secara bersama-sama dalam pengobatan COVID-19 terkonfirmasi derajat ringan hingga sedang pada pasien dewasa dan anak-anak usia di atas 12 tahun serta pasien berisiko tinggi yang berpotensi mengalami COVID-19 derajat berat.[1,7]
Bamlanivimab
Selain casirivimab dan imdevimab, bamlanivimab juga merupakan suatu antibodi monoklonal penetral anti-protein S yang telah mendapatkan izin penggunaan emergensi. Izin ini membatasi penggunaan bamlanivimab untuk pasien COVID-19 derajat ringan hingga sedang yang baru terdiagnosis dan belum pernah dirawat inap serta berisiko untuk mengalami COVID-19 derajat berat.
Otorisasi emergensi tersebut diberikan berdasarkan hasil penelitian bahwa progresivitas penyakit berkurang pada pasien yang mendapatkan terapi bamlanivimab dibandingkan plasebo pada uji klinis acak penyamaran ganda terkontrol plasebo yang dilakukan terhadap 465 pasien non rawat inap. Dosis pemberian bamlanivimab yang disarankan adalah 700 mg dengan cara pemberian intravena.[1,7,8]
Bamlanivimab-Etesevimab
Bamlanivimab juga telah dipelajari manfaatnya sebagai terapi kombinasi dengan etesevimab. Etesevimab merupakan suatu antibodi monoklonal anti-protein S dengan regio Fc yang dimodifikasi.
Bamlanivimab-etesevimab terbukti secara signifikan menurunkan viral load dibandingkan plasebo pada hari ketiga hingga ke-11 pasca terdiagnosis. Selain itu, terdapat penurunan proporsi pasien yang memerlukan rawat inap secara signifikan pada grup yang mendapatkan bamlanivimab-etesevimab dibandingkan plasebo (0,9% vs 5,8%). Terapi kombinasi antibodi monoklonal ini juga menurunkan risiko rawat inap hingga 70%, khususnya pada subgrup pasien rawat jalan dengan faktor risiko.
Berdasarkan data tersebut, FDA mengeluarkan otorisasi emergensi untuk penggunaan bamlanivimab-etesevimab pada pasien anak, termasuk neonatus, maupun dewasa dengan COVID-19 terkonfirmasi derajat ringan hingga sedang, dan pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami progresi menjadi COVID-19 derajat berat.
Otorisasi ini diberikan secara terbatas bagi pasien rawat jalan dan tidak dianjurkan bagi pasien rawat inap maupun pasien yang telah dirawat inap maupun pasien yang memerlukan terapi oksigen atau dukungan ventilator mekanik. Dosis pemberian yang disarankan untuk pasien dewasa dan anak-anak adalah 700 mg bamlanivimab dan 1400 mg etesevimab yang diberikan secara bersama-sama sebagai infus tunggal intravena.[1,7,8]
Antibodi Monoklonal yang Mengatur Milieu Sistem Imun
Antibodi monoklonal yang mengatur milieu sistem imun dapat dipertimbangkan sebagai terapi bagi pasien COVID-19 derajat berat. Imunopatogenesis COVID-19 sangat dipengaruhi peran GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) yang dihasilkan oleh sel T CD4 yang teraktivasi dan interleukin-6 (IL-6). Kedua molekul ini membantu meningkatkan perekrutan monosit dan makrofag sehingga berkontribusi terhadap badai sitokin.
Istilah badai sitokin dapat diartikan sebagai reaksi berlebihan sistem imun yang ditandai oleh pelepasan IL-6, IL-1, IL-2, IL-8, TNF-α, dan mediator inflamasi lainnya. Pelepasan sitokin secara berlebihan dapat mengaktifkan sistem imun untuk melepaskan radikal bebas sehingga berkontribusi terhadap sindrom distres pernapasan akut, kegagalan multiorgan, dan kematian.[7,9]
Walaupun karakteristik badai sitokin pada COVID-19 belum diketahui dengan pasti, antibodi monoklonal yang menargetkan sitokin diduga berperan penting dalam penanganan COVID-19 derajat berat. Sejumlah inhibitor IL-6 seperti tocilizumab, sarilumab, dan siltuximab telah mulai dipelajari pada berbagai penelitian klinis.[7,9,10]
Tocilizumab
Data dari berbagai uji klinis mengisyaratkan bahwa tocilizumab berdampak secara signifikan terhadap penurunan risiko kematian akibat COVID-19. Dalam sebuah tinjauan sistematik, Yu et al mempelajari 17 uji klinis yang mencakup 8614 partisipan untuk mengetahui efikasi tocilizumab pada COVID-19. Berdasarkan analisis tersebut, Yu et al menemukan bahwa pemberian tocilizumab berkaitan secara signifikan terhadap penurunan mortalitas umum pada 28 hari dibandingkan terapi standar atau plasebo.
Selain itu, tocilizumab juga menurunkan risiko pasien untuk memerlukan ventilasi mekanik invasif hingga 21%. Secara spesifik, penelitian Yu et al mengungkapkan bahwa subgrup pasien yang paling mendapatkan manfaat adalah pasien dengan COVID-19 derajat sedang hingga berat. Kelompok pasien ini juga paling signifikan mengalami penurunan risiko terhadap kebutuhan ventilasi mekanik.[7,9,10]
Dosis, Waktu, dan Durasi Pemberian:
Heterogenitas antar studi yang cukup tinggi menimbulkan tantangan dalam menentukan dosis, waktu dan durasi pemberian tocilizumab. Secara umum, pedoman merekomendasikan pemberian tocilizumab dosis tunggal 8 mg/kg dengan dosis maksimal 800 mg yang diberikan melalui infus intravena selama 60 menit, yang dikombinasikan dengan pemberian dexamethasone atau kortikosteroid yang ekivalen.
Apabila gejala dan tanda klinis pasien menunjukkan perburukan atau tidak tampak perbaikan setelah dosis pertama, pemberian satu dosis tambahan dapat dipertimbangkan dengan jarak 8 jam sejak pemberian infus tocilizumab pertama. Berdasarkan izin penggunaan emergensi yang dikeluarkan untuk tocilizumab, obat hanya diberikan untuk pasien berusia di atas 2 tahun yang mendapat terapi kortikosteroid sistemik dan memerlukan terapi oksigen, ventilasi mekanik invasif atau non invasif, atau oksigenasi membran ekstrakorporeal (ECMO).[9,10]
Sarilumab
Pada meta analisis yang sama, Yu et al mempelajari efikasi antibodi monoklonal anti-sitokin lain, yakni sarilumab. Pada penelitian tersebut, sarilumab tidak berdampak secara signifikan terhadap luaran klinis tingkat kematian dan kebutuhan terhadap ventilator mekanik. Hal ini mungkin berkaitan dengan sedikitnya jumlah uji klinis dan populasi pasien yang berkaitan dengan terapi sarilumab.[10]
Tantangan Penggunaan Antibodi Monoklonal pada COVID-19
Tantangan penggunaan antibodi monoklonal pada COVID-19 meliputi kemunculan strain virus resisten antibodi monoklonal, keterbatasan akses dan biaya, serta kemunculan varian virus baru.[1,7]
Resistensi Virus
Resistensi terhadap antibodi monoklonal yang berikatan dengan protein S dapat terjadi sebelum terapi maupun akibat terapi (treatment-emergent).
Di Amerika Serikat, varian SARS-CoV-2 dengan kerentanan yang rendah terhadap bamlanivimab telah terdeteksi dan ditemukan pada 20% kasus di beberapa wilayah. Atas temuan ini, FDA menarik otorisasi emergensi monoterapi bamlanivimab, tetapi tetap mempertahankan izin penggunaan emergensi bagi kombinasi bamlanivimab-etesevimab. Berdasarkan pengalaman tersebut, berbagai studi dilakukan untuk mempelajari hubungan antara kemunculan varian SARS-CoV-2 baru dan resistensi terhadap antibodi monoklonal.[1]
Keterbatasan Akses dan Biaya
Keterbatasan akses dan biaya juga menjadi tantangan yang signifikan dalam penerapan penggunaan antibodi monoklonal pada COVID-19. Harga jual antibodi monoklonal masih tergolong sangat tinggi dan sangat dipengaruhi oleh tingginya biaya penelitian dan pengembangan. Selain itu, penelitian dan pengembangan antibodi monoklonal masih sangat bergantung pada institusi penelitian di luar Indonesia sehingga upaya pemindahan produk obat dari luar ke dalam negeri membuat harga obat ini semakin tinggi.[1,7]
Kemunculan Strain Baru
Kemunculan varian virus baru sangat berpotensi membuat terapi antibodi monoklonal menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti umumnya menganjurkan pendekatan terapi antibodi monoklonal kombinasi alih-alih monoterapi sebab terapi kombinasi mampu berikatan dengan epitop berbeda yang diperkirakan dapat menurunkan kemunculan varian resisten imbas terapi.
Pendekatan lain yang dapat dipertimbangkan adalah memilih antibodi monoklonal penetral yang menargetkan epitop yang penting untuk fungsi virus namun belum terbukti mengalami mutasi.[4]
Kesimpulan
Antibodi monoklonal sebagai terapi COVID-19 berperan dengan cara menetralisir SARS-CoV-2 masuknya virus ke dalam sel atau mengatur kondisi sistem imun sehingga tidak menimbulkan kerusakan lebih berat pada jaringan.
Meskipun antibodi monoklonal terhadap COVID-19 menunjukkan beberapa kemanjuran pada awal pandemi, kemanjuran ini telah dilaporkan menurun karena virus telah berevolusi. Varian baru virus dari omicron dan seterusnya telah mengubah situs pengikatan antigen, yang berarti bahwa antibodi monoklonal tidak lagi efektif. FDA telah menghapus persetujuan dari penggunaan antibodi monoklonal untuk COVID-19. Antibodi monoklonal juga tidak lagi direkomendasikan dalam protokol pengobatan COVID-19.