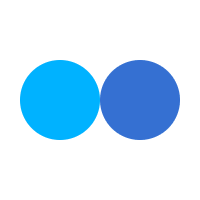Pemberian obat racikan atau disebut puyer berisiko baik dari segi ketepatan dosis, efektivitas biaya, maupun efisiensi waktu. Peracikan obat umumnya bertujuan untuk membantu pasien mendapatkan obat yang tidak mudah ditemukan di pasaran. Pola peracikan obat di apotek maupun farmasi rumah sakit telah jauh berubah dalam beberapa dekade terakhir dan turut dipengaruhi oleh perubahan regulasi terkait praktik peracikan obat.
Walaupun peracikan obat mungkin diperlukan bagi pasien tertentu, beberapa risiko perlu diidentifikasi dan dicegah untuk menghindari dampak peracikan obat yang dapat memengaruhi keselamatan pasien, termasuk bahaya dari polifarmasi pada pasien anak.[1–3]
Sekilas tentang Obat Racikan
Obat racikan atau puyer adalah obat yang disiapkan sesuai kaidah peracikan untuk memenuhi kebutuhan medis spesifik pasien, di luar lisensi penggunaan obat tersebut. Peracikan obat di luar indikasi yang tertera dalam brosur obat didorong oleh kebutuhan terapi pasien dengan penyakit langka akibat keterbatasan sediaan obat di pasaran.[1–3]
Misalnya, pada pasien anak yang menderita Addison disease. Mengingat fludrocortisone hanya tersedia dalam formulasi tablet, obat ini dapat diracik dalam bentuk sirup agar memudahkan administrasi dan penentuan dosis.
Selain itu, obat-obatan dermatologis dengan kandungan bahan aktif juga sering diracik menjadi satu krim untuk memudahkan aplikasi pada pasien. Misalnya, dapson, asam retinoat, dan asam azalea sering diracik menjadi krim akne. Dengan begitu, pada beberapa situasi khusus, praktik peracikan obat di luar lisensi penggunaan masih dapat dilakukan demi kebutuhan pasien.[1–3]
Tren Peracikan Obat
Seiring meningkatnya produksi obat terstandar, praktik peracikan obat di farmasi komunitas telah jauh menurun, tetapi meningkat di farmasi rumah sakit. Pada dekade 1930, hampir 75% resep yang masuk ke farmasi komunitas memerlukan proses peracikan obat.
Angka ini berangsur-angsur menurun hingga 25% pada tahun 1950-an, 5% pada dekade 1960, dan 1% pada dekade 1970. Sebaliknya, kebutuhan peracikan obat di farmasi rumah sakit meningkat pada kurun waktu yang sama dan berkaitan dengan pemberian kemoterapi, nutrisi parenteral, dan bedah jantung yang sering memerlukan pemberian zat kardioplegik.[4]
Di sisi lain, data retrospektif pola peresepan obat di farmasi rumah sakit menunjukkan bahwa tingkat peresepan obat racikan sangat kecil bila dibandingkan peresepan obat nonracikan. McPherson et al. menemukan bahwa persentase pemberian obat racikan untuk pasien yang memiliki asuransi komersial berkisar antara 6,7–6,9%. Padahal, angka ini jauh melampaui penambahan jumlah pasien yang bergabung dengan asuransi komersial.
Selain itu, rerata biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan obat racikan adalah 30% lebih tinggi daripada obat nonracikan. Dengan kata lain, peracikan obat berpotensi meningkatkan pengeluaran biaya kesehatan yang dibebankan terhadap pasien maupun asuransi kesehatan.[5]
Manfaat dan Risiko Obat Racikan
Pertimbangan manfaat dan risiko obat racikan sangat tergantung pada dasar keputusan peracikan obat. Di satu sisi, peracikan obat tradisional dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan medis pasien tertentu yang tidak dapat dipenuhi dengan obat komersial.
Di sisi lain, terdapat laporan yang menyebutkan bahwa peracikan obat nontradisional memiliki potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat ditemukan pada peracikan obat dalam jumlah besar yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Food and Drug Administration (FDA).
Praktik ini umumnya bertujuan menjual obat dalam skala besar dan memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, regulasi yang ditetapkan pemerintah merupakan kunci untuk menyeimbangkan antara menyediakan kebutuhan pasien dengan kondisi medis tertentu dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat racikan.[6,7]
Risiko Kesalahan Peracikan Obat
Risiko lain yang dapat timbul akibat penggunaan obat racikan adalah kesalahan peracikan obat. Watson et al mengelompokkan kesalahan peracikan obat menjadi tiga kategori, yaitu kontaminasi, suprapotensi, dan subpotensi.
Pada proses peracikan obat, kontaminasi dapat terjadi pada produk yang diproduksi dan dibagikan secara massal, khususnya obat yang diberikan secara parenteral. Obat yang terkontaminasi flora lingkungan dapat masuk ke dalam tubuh pasien dan menyebabkan luaran klinis yang buruk bagi pasien.
Sejumlah kasus telah dilaporkan akibat praktik peracikan obat dalam jumlah besar, seperti meningitis fungal di Tennessee, meningitis bakterial di California, serta kontaminasi Streptococcus di Nashville dan Los Angeles.
Kontaminasi pada obat racikan yang didistribusikan secara massal akan berdampak besar sebab jaringan distribusi obat ini biasanya cukup luas dan bersifat lintas wilayah.[4,6]
Suprapotensi dan subpotensi merupakan kesalahan peracikan obat yang terjadi akibat sediaan kekuatan obat yang berbeda-beda. Akibatnya, dosis obat menjadi kurang atau lebih dibandingkan batasan yang wajar. Subpotensi pernah terjadi pada kasus konsentrasi tacrolimus subterapeutik yang menyebabkan penurunan kadar tacrolimus serum dan reaksi penolakan organ transplan pada populasi anak.
Sementara itu, suprapotensi pernah tercatat pada beberapa jenis obat yang diracik oleh apotek 503A (apotek dengan izin peracikan terbatas berdasarkan resep individual) di Amerika Serikat. Penelusuran lanjutan mengungkapkan bahwa kesalahan konsentrasi obat racikan memiliki pola kelipatan yang diduga terjadi akibat kesalahan penghitungan dosis. Untuk perhitungan dosis obat anak, sebaiknya dokter menggunakan berat badan ideal atau aktual sesuai jenis obatnya, apakah obat lipofilik atau hidrofilik.[4,8]
Manfaat dan Risiko dari Aspek Ekonomi
Ditinjau dari sisi ekonomi, peracikan obat memiliki potensi manfaat dan risiko yang saling berkaitan. Pada beberapa wilayah, penyediaan fasilitas peracikan obat yang dipantau ketat oleh pemerintah dapat menjadi solusi keterbatasan akses obat tertentu. Peneliti di Indiana University memperkirakan bahwa strategi seperti ini dapat menghemat biaya obat tahunan hingga 25%.[7]
Sementara itu, asumsi yang sama belum tentu dapat diterapkan dalam praktik peracikan obat berskala kecil, seperti pada farmasi rumah sakit. Walaupun bahan baku obat racikan dapat diperoleh dengan harga terjangkau, tetapi sumber daya, waktu, pelatihan, dan peralatan yang dibutuhkan dapat meningkatkan biaya. Dengan begitu, harga obat menjadi lebih mahal hingga 30% melebihi harga obat nonracikan.
Selain itu, sejumlah asuransi mungkin memiliki klausul pengecualian reimbursement bagi pasien yang mendapatkan obat racikan. Dalam hal ini, pasien perlu menyiapkan sejumlah uang untuk membeli obat racikan dan dapat berdampak pada ekonomi pasien.[5,7]
Regulasi Internasional dan Nasional terkait Peracikan Obat
Regulasi internasional dan nasional wajib dipatuhi terkait pembuatan dan peresepan obat racikan. Dalam Pasal 503A dan 503B FDCA (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act), FDA mengatur tentang peracikan obat pada apotek penyelenggara obat racikan, apotek di rumah sakit, dan praktik dokter pribadi.
Regulasi Internasional terkait Peracikan Obat
Dalam Pasal 503A FDCA, dijelaskan bahwa proses peracikan obat hanya dilakukan setelah apotek menerima resep individual dari pasien dan obat hanya dapat disediakan dalam jumlah terbatas (maksimal untuk 30 hari). Apotek yang berhak melakukan peracikan obat harus memiliki izin peracikan obat yang dikeluarkan oleh negara bagian dan wajib mematuhi standar USP (United States Pharmacopeia) dan Formularium Nasional Amerika Serikat.
Sementara itu, Pasal 503B FDCA yang mengatur tentang fasilitas pengembangan fasilitas alih daya yang diizinkan untuk mengelola proses peracikan obat semakin memperkuat pengaturan supervisi terhadap proses peracikan dalam jumlah besar.
Akan tetapi, penambahan kedua pasal dalam FDCA ini mendapat kritik dari apoteker dan dokter di Amerika Serikat karena dianggap menghalangi kemampuan mereka untuk meracik obat yang penting bagi pengobatan pasien. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua pasal tersebut memengaruhi praktik pemberian obat racikan di Amerika Serikat.[4,11]
Apabila terjadi pelanggaran berupa ketidaklengkapan pencatatan kegiatan pencampuran dan dilusi obat, nomor lot obat yang dicampur, dan ketidakpatuhan pemusnahan obat yang melewati batas waktu rekonstitusi atau penyimpanan, dokter yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi denda, pidana penjara 1–3 tahun, atau keduanya.
Oleh sebab itu, penerapan Pasal 503A dan 503B FDCA telah meningkatkan kewaspadaan para profesional untuk mematuhi peraturan lokal dan nasional terkait peracikan obat dalam praktik klinis sehari-hari.[4,7]
Regulasi Nasional terkait Peracikan Obat
Di Indonesia, regulasi peracikan obat terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 58 Tahun 2014 Bab III, yaitu tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Permenkes 35 tahun 2014 Bab III-IV, yaitu tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.[4,9,10]
Permenkes 35 dan 58 Tahun 2014 menyebutkan bahwa peracikan obat merupakan salah satu kegiatan pelayanan farmasi klinik yang diselenggarakan apotek maupun farmasi rumah sakit.
Dalam petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, telah diatur mengenai persyaratan teknis peracikan, alat, bahan, tata laksana, dan evaluasi proses peracikan obat baik di farmasi rumah sakit maupun apotek.
Secara khusus, dalam petunjuk teknis tersebut diatur bahwa proses peracikan sediaan steril dilakukan oleh apoteker yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kemampuan penyusunan prosedur pencampuran sediaan steril.[9,10,12,13]
Walaupun peracikan obat merupakan salah satu kompetensi wajib yang dimiliki oleh apoteker, pada kondisi tertentu, peracikan obat diizinkan untuk dilakukan oleh dokter sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi berwenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien apabila berpraktik di daerah terpencil yang tidak memiliki apotek.
Dalam UU Nomor 69 tahun 2009, diatur juga mengenai praktik kefarmasian yang wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter pada situasi tertentu, serta sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar. Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam menjaga keselamatan pasien dari praktik peracikan obat yang tidak sesuai ketentuan.
Akan tetapi, ketentuan perundang-undangan ini belum menjelaskan secara rinci sejauh mana praktik peracikan obat yang diizinkan untuk dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Beberapa hal lain juga belum diatur dalam regulasi yang ada, seperti standarisasi tingkat pelatihan untuk meracik obat dan regulasi peracikan obat di klinik untuk prosedur klinis sederhana. Pengaturan ini penting, mengingat penyediaan SDM kefarmasian tidak selalu mudah dilakukan di daerah tertentu.[14,15]
Kesimpulan
Peracikan obat merupakan salah satu praktik kefarmasian yang masih diperlukan bagi pasien dengan kebutuhan medis tertentu. Akan tetapi, beberapa potensi penyalahgunaan praktik peracikan obat, seperti peracikan obat secara massal untuk keuntungan finansial serta peracikan obat yang tidak mengindahkan kaidah keselamatan pasien, perlu diantisipasi secara serius.
Kesalahan peracikan obat yang disebabkan oleh kontaminasi, suprapotensi, dan subpotensi perlu dihindari karena dapat menyebabkan risiko yang signifikan pada pasien.
Beberapa Undang-Undang di Indonesia telah mengatur tentang tenaga kesehatan yang berwenang dan kompeten melakukan peracikan obat secara umum maupun pada situasi khusus, seperti di daerah terpencil. Akan tetapi, penyempurnaan regulasi terkait standarisasi pelatihan untuk praktik peracikan obat serta pengaturan praktik peracikan obat di klinik untuk prosedur klinis sederhana perlu dibahas lebih lanjut untuk menjamin keselamatan pasien.
Direvisi oleh: dr. Felicia Sutarli