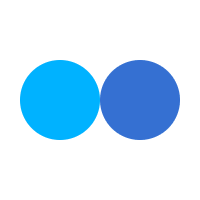Pemilihan terapi alergi untuk ibu menyusui perlu mempertimbangkan aspek keamanan pada bayi yang disusui. Proses menyusui mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal, sehingga dianjurkan untuk dilakukan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Namun, pada kenyataannya, proses menyusui kadang dihentikan lebih awal karena adanya kekhawatiran terkait obat yang digunakan ibu.[1,2]
Proses menyusui memberikan manfaat tidak hanya bagi bayi tetapi juga bagi ibu. Pada bayi, ASI dapat mengurangi risiko infeksi dan alergi, mengurangi risiko obesitas, dan membantu perkembangan kognitif. Sementara itu, pada ibu, menyusui dapat membantu pemulihan pascapersalinan lebih cepat dan menurunkan risiko kanker, osteoporosis, serta diabetes tipe 2. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk memilih terapi alergi yang aman untuk ibu menyusui agar proses menyusui dapat tetap dilanjutkan.[1,2]
Alergi, khususnya rhinitis alergi (hay fever), merupakan salah satu penyakit kronis yang memengaruhi 20–30% populasi wanita usia subur. Salah satu obat yang paling umum digunakan untuk terapi alergi adalah antihistamin. Studi berbasis populasi menunjukkan bahwa sekitar 2–3% wanita mendapatkan resep antihistamin dalam 3 bulan pertama setelah persalinan. Oleh sebab itu, penting untuk memilih antihistamin yang aman untuk bayi tanpa mengorbankan efektivitas terapi alergi pada ibu.[2-4]
Faktor yang Memengaruhi Transfer Obat ke ASI dan Efeknya pada Bayi
Obat-obatan masuk dari plasma ke ASI melalui proses difusi pasif (mayoritas), difusi terfasilitasi, dan transportasi aktif, sehingga konsentrasi obat dalam ASI tergantung pada konsentrasi obat dalam plasma ibu dan karakteristik difusi.[1,4]
Difusi pasif tergantung pada gradien konsentrasi antara plasma ibu dan ASI, di mana obat-obat lipofilik dan tidak terionisasi bisa berpindah dengan mudah. Difusi terfasilitasi melibatkan protein pembawa yang membantu pergerakan molekul tertentu melintasi membran sel. Molekul tersebut dapat berupa zat gizi esensial, tetapi juga dapat berupa obat-obat yang digunakan oleh ibu.[4]
Jumlah obat yang diekskresikan ke dalam ASI tergantung pada beberapa faktor kinetik, yaitu kelarutan obat dalam lemak, ukuran molekul obat, konsentrasi obat dalam ASI, ikatan protein obat dalam sirkulasi maternal, volume obat yang dikonsumsi, waktu paruh obat, dan penyerapan saluran cerna. Sejatinya, hanya sedikit obat yang secara aktif ditransportasi ke ASI.[1,2,4,6]
Kondisi kesehatan bayi dapat memengaruhi efek dari paparan obat. Paparan yang lebih kecil dapat signifikan pada bayi prematur yang memiliki kemampuan metabolisme obat lebih rendah. Paparan obat yang sama mungkin kurang berisiko pada bayi matur.[1]
Strategi untuk meminimalkan paparan obat terhadap bayi dapat berupa pemberian dosis setelah menyusui dan sebelum interval tidur terpanjang untuk obat yang diminum sekali sehari. Obat dengan penyerapan oral yang buruk, kelarutan lipid yang rendah, dan ikatan protein yang tinggi adalah yang paling aman.[1]
Parameter untuk Menilai Keamanan Paparan Obat terhadap Bayi yang Disusui
Faktor-faktor tersebut di atas menentukan milk-to-plasma ratio (rasio MP), yang akan memengaruhi besarnya paparan obat ke bayi melalui ASI. Parameter penting untuk menilai keamanan dan jumlah kuantitatif obat yang memapar bayi adalah relative infant dose (RID), dengan nilai <10% umumnya dianggap aman bagi bayi menyusui.[4]
Rasio MP menentukan sejauh mana obat berpindah dari plasma ibu ke ASI. Rasio ini dihitung dengan membagi konsentrasi obat dalam ASI dengan konsentrasi obat dalam plasma ibu. Kelebihan rasio ini adalah perhitungannya yang sederhana dan bermanfaat sebagai analisis awal untuk menilai apakah obat kemungkinan besar memiliki jumlah signifikan dalam ASI. Namun, kekurangannya adalah hasil amat bervariasi tergantung pada waktu pengambilan sampel relatif terhadap waktu pemberian obat.[4]
Di lain sisi, RID adalah penilaian keamanan paparan obat pada bayi yang disusui. RID didefinisikan sebagai persentase dosis obat ibu yang ditransfer ke bayi melalui ASI.[4]
RID = Dosis bayi melalui ASI (mL/kg/hari)
Dosis ibu (mL/kg/hari)
Untuk menganalisis RID, tentukan dosis bayi dengan mengukur konsentrasi obat dalam ASI dan memperkirakan volume ASI yang dikonsumsi bayi per hari. Selanjutnya, dosis ibu dihitung berdasarkan berat badan ibu dan dosis obat yang diterima. Secara umum, RID <10% dianggap aman dan menunjukkan risiko minimal bagi bayi. Namun, ambang ini dapat bervariasi tergantung farmakokinetik obat dan kondisi kesehatan bayi. Dalam beberapa kasus, RID yang lebih rendah (seperti 5%) juga dapat dijadikan acuan.[4]
Mengetahui RID Berbagai Antihistamin
Beberapa studi antihistamin telah menghitung RID (Tabel 1). Antihistamin dengan nilai RID terendah adalah terfenadine (0,3%) dan RID tertinggi adalah clemastine (4,5%). Untuk epinastine, RID berkisar antara 0,4–2,5%, sedangkan untuk cetirizine, ebastine, loratadine, dan triprolidine semuanya <2%.[2]
Tabel 1. Konsentrasi Antihistamin dalam Plasma dan ASI
| Zat | RID (%) |
| Cetirizine | 1,8 |
| Clemastine | 4,5 (dari Cmean) |
| Ebastine | 0,5 (termasuk carebastine) |
| Epinastine | 0,4–2,5 |
| Loratadine | 1,1 (termasuk desloratadine) |
| Terfenadine | 0,3 |
| Triprolidine | 0,9 |
Sumber: Ngo E, et al. 2022.
Perbandingan Antihistamin Generasi Pertama dan Kedua
Histamin dilepaskan oleh sel mast dan basofil sebagai respons terhadap alergen atau infeksi, yang kemudian menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan perpindahan cairan dari kapiler ke jaringan sekitarnya. Akibatnya terjadi pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah yang memunculkan gejala alergi. Antihistamin dapat menghentikan efek ini dengan bertindak sebagai antagonis pada reseptor H-1. Manfaat klinisnya adalah pengurangan gejala alergi.[5]
Antihistamin generasi pertama menembus sawar darah-otak dan menghambat reseptor H-1 di otak, sehingga menghasilkan efek samping yang berbeda dengan antihistamin generasi kedua yang secara selektif mengikat reseptor histamin di perifer.[5]
Antihistamin Generasi Pertama
Antihistamin generasi pertama bersifat sedatif, contohnya dimenhydrinate, doxylamine, pheniramine, diphenhydramine, chlorpheniramine, brompheniramine, dan hydroxyzine. Beberapa laporan menunjukkan efek samping iritabilitas, kolik, dan kantuk pada bayi, meskipun kasusnya jarang dan tidak memerlukan intervensi. Karena sifat sedatifnya, antihistamin generasi pertama sudah jarang dianjurkan.[7]
Antihistamin Generasi Kedua
Antihistamin generasi kedua lebih disukai karena nonsedatif (tidak menyebabkan efek samping pada saraf pusat). Contoh antihistamin generasi kedua adalah loratadine, desloratadine, cetirizine, dan fexofenadine. Obat-obat ini menunjukkan transfer yang sangat rendah ke dalam ASI (RID <5%).[4,7]
Studi farmakokinetik loratadine dan desloratadine memperkirakan paparan terhadap bayi hanya 1,1% dari dosis ibu, sedangkan paparan fexofenadine hanya sekitar 0,45%. Efek samping sangat minimal, sehingga kelompok ini direkomendasikan sebagai pilihan pertama untuk ibu menyusui.[4,7]
Studi terkait Efek Samping Antihistamin terhadap Bayi yang Disusui
Saat ini bukti terkait efek samping obat atau adverse drug reactions (ADR) pada bayi yang terpapar antihistamin melalui ASI masih terbatas. Ada empat studi yang meneliti kemungkinan ADR pada bayi, yakni berupa satu laporan kasus terkait clemastine, dua studi farmakokinetik mengenai epinastine dan loratadine, serta satu studi tindak lanjut mengenai antihistamin secara umum.[2]
Dari studi-studi tersebut, tampak bahwa tingkat paparan antihistamin dari ASI terhadap bayi sebenarnya cukup rendah. Semua antihistamin yang diteliti menunjukkan dosis absolut bayi <10 µg/kg/hari. Sebagian besar studi tidak menemukan ADR pada bayi. Laporan ADR hanya muncul pada penggunaan clemastine. Seorang bayi berusia 10 minggu menunjukkan gejala mengantuk, menolak menyusu, dan menangis bernada tinggi. Namun, kasus ini dibarengi penggunaan phenytoin dan carbamazepine oleh ibu, sehingga sulit dipastikan apakah gejala tersebut murni akibat clemastine.[2]
Faktor usia bayi penting. Reaksi lebih sering terjadi pada bayi berusia sangat muda (<2 bulan), yang memiliki metabolisme obat lebih lambat. Bayi di atas 4 bulan dalam studi ini umumnya tidak menunjukkan ADR.[2]
Studi yang menilai antihistamin secara umum menemukan bahwa 8 dari 85 bayi yang terpapar mengalami gejala ringan yang dianggap ADR. Iritabilitas merupakan gejala yang tersering. Namun, tidak ada bayi yang memerlukan intervensi medis dan tidak ada studi yang menilai gejala tersebut sebagai gejala yang bermakna secara klinis.[2]
Kesimpulan
Sebagian besar antihistamin dinilai aman digunakan oleh ibu menyusui karena hanya diekskresikan dalam jumlah sedikit ke dalam ASI. Antihistamin generasi kedua lebih direkomendasikan karena konsentrasi yang rendah dalam ASI dan risiko efek samping yang lebih rendah pada bayi. Antihistamin generasi pertama bersifat sedatif dan lebih baik dihindari oleh ibu menyusui, terutama dalam jangka panjang.
Saat ini bukti terkait efek samping pada bayi akibat penggunaan antihistamin oleh ibu memang masih terbatas. Namun, bukti yang ada menunjukkan bahwa risiko meningkat pada bayi yang berusia sangat muda atau bayi prematur. Oleh sebab itu, penggunaan antihistamin oleh ibu perlu lebih berhati-hati pada kondisi tersebut.
Untuk semakin meminimalkan risiko, waktu pemberian obat dapat disesuaikan setelah menyusui atau sebelum periode tidur terpanjang bayi untuk meminimalkan paparan.