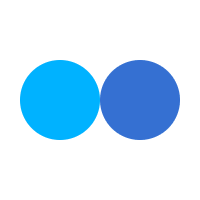Sepsis intraabdominal merupakan entitas klinis dari sindrom sepsis yang berkembang di organ intraabdominal yang disebabkan oleh infeksi intraperitoneal (peritonitis). Peritonitis dapat diklasifikasikan berdasarkan integritas anatomi dari rongga perut. Peritonitis primer merupakan kondisi peritonitis dengan organ intraabdomen yang tidak rusak. Peritonitis primer juga dikenal sebagai peritonitis bakterial spontan dan diobati tanpa intervensi bedah.[1-3]
Sumber infeksi sering kali sulit ditentukan dan biasanya ditemukan terjadi pada bayi dan pasien sirosis. Peritonitis sekunder adalah infeksi pada rongga peritoneum akibat adanya perforasi organ viskus berongga, kebocoran anastomosis, nekrosis iskemik, atau cedera pada saluran cerna. Peritonitis sekunder merupakan kejadian yang umum pada pasien bedah kritis. Peritonitis tersier didefinisikan sebagai infeksi intraabdomen berulang atau persisten yang serius setelah pengendalian peritonitis sekunder yang awalnya tampak berhasil.[4,5,6]
Prevalensi jumlah sepsis intraabdominal yang ditemukan di enam rumah sakit tersier di Indonesia pada pertengahan tahun 2017 adalah sekitar 10%, dengan angka mortalitas 16,6%. Dokumentasi sepsis intraabdominal yang akurat masih menjadi kendala utama dalam menentukan prevalensi sepsis intraabdominal di Indonesia.
Hal tersebut terjadi karena diagnosis sepsis intraabdominal tidak terdokumentasi dengan jelas dalam rekam medis dan bukan merupakan diagnosis yang terdaftar dalam International Classification of Diseases revisi kesepuluh (ICD-10). Akibat dari heterogenitas dalam manajemen sepsis, angka kematian akibat sepsis intraabdominal masih tinggi, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, yang terlihat dalam angka 3–42%.[7,8]
Oleh karena masih tingginya angka kematian akibat sepsis intraabdominal ini, maka dikembangkan pedoman untuk meningkatkan manajemen sepsis intrabdominal agar angka mortalitas dan morbiditas dapat ditekan, khususnya di Indonesia. Tujuan dari pedoman yang dibuat khusus di Indonesia adalah untuk membahas karakteristik khusus Indonesia, yang ternyata berbeda dari negara maju.
Kebanyakan kasus sepsis intraabdominal yang ada di Indonesia merupakan kondisi yang lanjut dengan penanganan awal yang terlambat. Pada ulasan kali ini, akan dibahas mengenai pedoman sepsis intraabdominal dalam perspektif Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik pasien orang Indonesia, asal-usul penyakit terkait dengan geografi (negara kepulauan), status ekonomi, serta kepercayaan atau budaya.
Di samping itu, penundaan pengobatan dari penyedia medis/kesehatan di pusat perawatan primer/sekunder (termasuk keterlambatan diagnosis karena sumber daya yang terbatas) adalah hal yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga, terkadang pedoman dari negara maju tidak sesuai dengan karakteristik orang Indonesia dan tidak dapat diterapkan di Indonesia.[7-9]
Ulasan Pedoman Sepsis Intraabdominal di Indonesia
Pada tahun 2018, dibuat suatu pedoman sepsis intraabdominal (infeksi intraabdominal yang komplikata) khusus dalam perspektif Indonesia, yang merupakan adaptasi dari beberapa pedoman klinis dari luar negeri yang sudah diakui secara internasional.
Beberapa pedoman dirangkum dan disesuaikan dengan karakteristik di Indonesia. Rekomendasi dibuat berdasarkan hierarki berbasis bukti Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Selain itu, juga dilakukan peninjauan oleh Ikatan Ahli Bedah Digestif Indonesia (IKABDI) dan seorang ahli dari Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Pernyataan atau rekomendasi yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi Indonesia tidak diadaptasi. Persetujuan rekomendasi dilakukan dengan menggunakan metode Delphi.[7,10-12]
Rangkuman dari pedoman tersebut antara lain:
- Di Indonesia, semua kasus sepsis intraabdominal atau complicated intraabdominal infection (cIAI) yang ada di pusat rujukan (perawatan kesehatan tersier atau rumah sakit tipe A) dikategorikan sebagai cIAI berisiko tinggi, sedangkan yang dikelola di pusat perifer (perawatan kesehatan sekunder atau rumah sakit tipe C dan D) dikategorikan sebagai cIAI risiko rendah.
- Pemeriksaan fisik berperan penting dalam mengarahkan penilaian diagnostik dan rencana manajemen tindakan ahli bedah. Perlunya pemeriksaan laboratorium dan pencitraan sederhana tergantung pada temuan klinis, usia, dan sumber daya ketersediaan yang ada. Indikator klinis yang terpenting adalah sindrom sepsis secara klinis serta tanda dan gejala peritonitis.
- Kultur rutin mikroorganisme dan uji sensitivitas antibiotik direkomendasikan pada pasien dengan kondisi kritis dan berisiko tinggi, termasuk yang berisiko terinfeksi mikroorganisme resistan (riwayat penggunaan antibiotik spektrum luas). Sedangkan, kultur rutin mikroorganisme dan uji sensitivitas antibiotik tidak dianjurkan pada kasus risiko rendah.[7]
Kultur mikroorganisme dan uji sensitivitas antibiotik dari spesimen intraperitoneal direkomendasikan untuk dilakukan setiap prosedur laparotomi ulang (re-laparotomi). Hasil kultur dan uji sensitivitas antibiotik dari spesimen intraperitoneal ini digunakan sebagai dasar pemilihan antibiotik yang tepat untuk terapi.
Jaringan intraperitoneal dianggap sebagai spesimen yang representatif untuk tujuan diagnostik (dengan volume jaringan minimum 1–2 gram), yang diambil saat operasi dari organ yang terinfeksi. Perlu diperhatikan bahwa spesimen yang diambil dari produksi tabung drainase yang dipasang setelah laparotomi tidak memiliki nilai diagnostik, karena hanya merupakan kuman hasil kolonisasi.
- Perlu diingat bahwa leukositosis, peningkatan C-reactive protein (CRP) dan procalcitonin (PCT) adalah penanda respons inflamasi, tetapi tidak dapat membuktikan adanya infeksi.
- Pencitraan tidak digunakan secara rutin untuk mendeteksi patologi pada sepsis intraabdominal. Jika dapat dideteksi dengan jelas melalui pemeriksaan fisik abdomen, pencitraan tidak diperlukan. Namun, pencitraan diindikasikan jika hasil pemeriksaan fisik meragukan. USG abdomen merupakan metode pilihan pertama untuk mendeteksi pengumpulan cairan intraabdominal patologis. Jika tidak ditemukan pengumpulan cairan intraabdomen patologis pada ultrasonografi, dapat dilakukan pemindaian computed tomography (CT). Foto polos abdomen tegak dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran radiolusen di subdiafragma, yaitu puncak dari rongga intraabdomen, di mana udara bebas didistribusikan pada kondisi perforasi organ gastrointestinal bagian proksimal.
- Kontrol sumber infeksi melalui pembedahan harus dilakukan dalam waktu 24 jam setelah sepsis intraabdominal ditegakkan, kecuali ada bukti kuat bahwa perawatan nonbedah atau penundaan akan memberikan hasil yang lebih baik.
Prosedur laparotomi bertahap untuk mengendalikan sumber infeksi (disebut damage control surgery) dengan penutupan abdomen sementara harus dipertimbangkan pada pasien kondisi kritis, terutama pasien dengan prediksi kemungkinan hipertensi intraabdominal atau gangguan fisiologis yang parah.
Dalam prosedur laparotomi, debris dan kontaminan yang tampak harus dihilangkan, dilanjutkan dengan dilusi yang adekuat menggunakan cairan kristaloid, sebelum dilakukan penutupan abdomen.
- Laparotomi ulang terencana atau terjadwal (planned re-laparotomy) sebagai prosedur rutin harus dihindari pada pasien berisiko tinggi dan pasien dengan peritonitis berat, jika pengendalian sumber infeksi yang memadai dapat dicapai. Sedangkan, laparotomi ulang sesuai kondisi pasien (on demand re-laparotomy) lebih disarankan karena memberikan hasil yang lebih baik daripada laparotomi ulang terencana.[7]
- Agen antibiotik empiris harus diberikan secara intravena dalam waktu 1 jam setelah sepsis intraabdominal ditegakkan. Pemberian antibiotik harus sesuai dengan formularium nasional yang tersedia di Indonesia. Obat yang disarankan adalah meropenem, doripenem, imipenem-cilastatin sebagai terapi empiris pada sepsis intraabdominal risiko tinggi.
Tigecycline tidak dianjurkan sebagai terapi empiris untuk sepsis intraabdominal risiko tinggi, tetapi dapat dipertimbangkan hanya pada kondisi infeksi patogen yang resistan dan antibiotik lain terbukti tidak efektif. Pada sepsis intraabdominal risiko rendah, disarankan untuk menggunakan ertapenem.
- Antibiotik anaerob perlu diberikan jika terdapat riwayat penggunaan antibiotik aerob yang lama. Obat yang dianjurkan adalah metronidazole yang dikombinasikan dengan antibiotik lain untuk terapi empiris. Penggunaan clindamycin tidak dianjurkan, kecuali metronidazole tidak tersedia atau dikontraindikasikan.
- Pasien dianggap berisiko tinggi terjadi kegagalan terapi jika mengalami salah satu dari kondisi berikut:
- Riwayat rawat inap setidaknya selama 48 jam dalam periode 90 hari terakhir
- Riwayat perawatan di rumah oleh perawat profesional dalam 30 hari terakhir
- Riwayat terapi intravena, perawatan luka, terapi penggantian ginjal dalam 30 hari terakhir
- Riwayat terapi antibiotik spektrum luas dalam 90 hari terakhir
- Infeksi pascaoperasi
- Sepsis intraabdominal dengan sumber infeksi yang disebabkan oleh patogen resistan
- Ada potensi infeksi mikroorganisme resistan dan/atau oportunistik[7]
Kesimpulan
Sepsis intraabdominal merupakan kondisi mengancam nyawa dan perlu pedoman manajemen yang tepat. Selama ini, penatalaksanaan mengacu pada pedoman dari negara maju yang sering kali kurang sesuai untuk diadaptasikan di Indonesia.
Kebanyakan kasus sepsis intraabdominal yang ada di Indonesia adalah kasus dengan kondisi yang lanjut dengan penanganan awal yang terlambat. Selain itu, karakteristik pasien dan sumber daya pada fasilitas kesehatan di Indonesia juga berbeda dengan di negara maju. Oleh sebab itu, perlu pedoman sepsis intraabdominal yang khusus dalam perspektif Indonesia, mulai dari penegakan diagnosis hingga manajemen sepsis intraabdominal. [7]
Manajemen sepsis intraabdominal sebaiknya dilakukan di rumah sakit tipe A, terutama yang berisiko tinggi. Sindrom sepsis serta tanda dan gejala peritonitis merupakan indikator klinis untuk mendiagnosis sepsis intraabdominal. Jika hasil pemeriksaan fisik meragukan, pencitraan seperti USG, foto polos, dan CT scan dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis.
Kontrol sumber infeksi melalui pembedahan harus dilakukan dalam 24 jam setelah sepsis intraabdominal ditegakkan. Prosedur ini tidak dapat ditunda, kecuali ada bukti kuat bahwa perawatan nonbedah dapat memberikan hasil yang lebih baik. Antibiotik empiris seperti meropenem harus diberikan segera setelah diagnosis ditegakkan, dan dapat dikombinasikan dengan antibiotik anaerob seperti metronidazole, jika ada riwayat penggunaan antibiotik aerob yang lama.