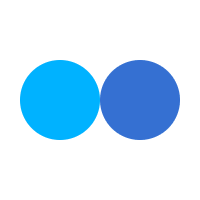Apakah pelatihan dapat meningkatkan respon tenaga kesehatan terhadap pasien korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)? Masih banyak tenaga kesehatan, termasuk dokter, yang merasa tidak nyaman atau tidak terbiasa untuk menggali riwayat pasien yang diduga sebagai korban KDRT, termasuk korban kekerasan pasangan intim (KPI). Sebaliknya, sebagian besar pasien KDRT dan KPI merasa kondisinya sebagai aib keluarga sehingga tidak akan menceritakan penyebab luka-luka dideritanya saat berobat.[1-3]
Seringkali tenaga kesehatan menjadi satu-satunya tempat bagi pasien KPI untuk mencari pertolongan, baik dokter, perawat, maupun bidan. Oleh karena itu, dirasakan perlu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai KPI, sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan pendekatan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pasien KPI.[1]
Gambaran KDRT di Indonesia
Laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia meningkat setiap tahunnya, termasuk kekerasan pasangan intim (KPI). Meskipun dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, kekerasan pasangan intim terutama dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.[1–3]
Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, 95% dari jumlah kekerasan pada perempuan dilakukan oleh pasangannya, dan meningkat dengan pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Meskipun demikian, diperkirakan laporan yang ada sebetulnya masih belum dapat merepresentasikan keadaan sebenarnya karena kebanyakan kasus tidak pernah dilaporkan, sehingga menciptakan fenomena gunung es.[2,3]
Isu KPI maupun KDRT di Indonesia masih dipandang biasa dan dianggap aib dalam keluarga. Hal ini yang menyebabkan perempuan biasanya menolak untuk melaporkan pengalamannya. Perempuan korban KPI biasanya tidak menceritakan bahwa kekerasan pasangannya sebagai sumber luka-luka yang dideritanya saat mencari pertolongan kesehatan.[1–3]
Dampak Buruk KDRT
Bentuk KPI maupun KDRT dapat berupa kekerasan psikologis, emosional, fisik, seksual, dan ekonomi. Kekerasan tersebut dapat menyebabkan cedera fisik dan mental, seperti luka/lebam, fraktur, cedera organ, depresi, ansietas termasuk gangguan cemas pada anak dan remaja, post traumatic stress disorder (PTSD), kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ginekologi, bahkan kematian. Masalah-masalah kesehatan akan berdampak lama setelah kekerasan terjadi.[1]
Peran Tenaga Medis dalam Kasus KDRT
Fasilitas kesehatan menjadi salah satu dari sedikit lokasi yang bisa didatangi perempuan secara mandiri tanpa ditemani. Pertemuan dengan tenaga kesehatan sebetulnya menjadi situasi yang ideal untuk mengidentifikasi dan memberi dukungan bagi pasien KDRT maupun KPI. Tenaga kesehatan perlu mengetahui cara skrining pasien KDRT pada setting rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lain.[1]
Tenaga kesehatan seharusnya dapat menjadi tempat pasien KPI mencari pertolongan. Namun, banyak pasien KPI yang tidak nyaman menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Jika tenaga kesehatan dapat menciptakan atmosfer yang nyaman dan mendukung, maka pasien diharapkan dapat terbuka akan pengalamannya. [3]
Selain menolong secara medis baik kondisi fisik dan psikis pasien, tenaga kesehatan juga memerlukan keterampilan dan pengetahuan untuk mengevaluasi kesiapan dan keinginan pasien untuk meninggalkan hubungan dengan kekerasan tersebut. Selanjutnya, tenaga kesehatan perlu mengetahui strategi berikutnya berdasarkan tingkat kesiapan pasien. Pada akhirnya, keberhasilan untuk keluar dari KPI sangat bergantung pada pasien sendiri. [4]
Pelatihan Penanganan Pasien KDRT bagi Tenaga Kesehatan
Saat ini, sudah tersedia berbagai pedoman klinis, pelatihan, atau kombinasi keduanya bagi tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi dan merespon kekerasan pasangan intim. Penelitian di Inggris menunjukkan bahwa advokasi untuk mengubah pola pikir korban KPI dapat berhasil apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah mendapat pelatihan sebelumnya.[3,4]
Sebuah tinjauan Cochrane pada tahun 2021 merangkum 19 penelitian mengenai pelatihan KPI bagi tenaga kesehatan di Amerika Serikat, Australia, Iran, Meksiko, Turki, dan Belanda. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelatihan KPI untuk tenaga kesehatan mungkin efektif sebagai prekursor perubahan perilaku dalam penanganan pasien KPI.[1]
Pelatihan meningkatkan pengetahuan dan respon tenaga kesehatan terhadap pasien KPI. Pelatihan KPI mencakup definisi dan tipe, faktor risiko dan prevalensi, serta pembahasan mengenai mitos dan misinformasi yang umum beredar. Pelatihan kemudian diikuti dengan skenario klinis dengan probandus.[1]
Bentuk pelatihan tersebut memungkinkan tenaga kesehatan berlatih memberikan konsultasi dan dukungan kepada pasien mengenai pengalaman kekerasan yang dialami, mendokumentasikan kekerasan yang terjadi, mendiskusikan upaya mencari perlindungan, dan merujuk pasien ke pelayanan yang menaungi perempuan dan korban kekerasan.[1,4]
Namun, hasil tinjauan Cochrane menyebutkan bahwa efek jangka panjang pelatihan (lebih dari) 12 bulan belum diketahui. Selain itu, terdapat beberapa risiko bias, yaitu tingkat heterogenitas substansial, proses randomized dan blinded peserta, serta pengurangan dalam banyak penelitian. Sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menilai dampak pelatihan KPI pada perilaku tenaga Kesehatan demi keselamatan pasien korban KPI.[1]
Pelatihan Penanganan Pasien KDRT di Indonesia
Sayangnya, belum ada laporan penelitian mengenai pelatihan penanganan pasien KDRT bagi tenaga Kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2019, WHO mengeluarkan panduan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam melayani perempuan korban kekerasan. Namun, panduan ini perlu divalidasi agar dapat diaplikasikan di Indonesia, intervensi yang dianjurkan seringkali sulit diaplikasikan di negara berkembang, dikarenakan kapasitas manusia, finansial, dan logistik yang jelas berbeda.[3,4]
Indonesia sebetulnya telah memiliki Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Selain itu, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga bekerja sama dengan United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) untuk merumuskan protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.[5]
Protokol yang tersedia berupa pengaduan, pemberian layanan pendampingan, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan ke rumah aman, layanan psikososial, layanan konsultasi hukum, dan pendampingan proses hukum.[5]
Namun sayangnya, implementasi pedoman-pedoman tersebut masih mengalami banyak kendala. Terdapat dua alasan utama yang menghalangi implementasinya, yaitu korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan dan bukti yang kurang. Beberapa alasan korban mencabut pengaduan adalah ketergantungan ekonomi korban pada pelaku, takutnya korban terhadap ancaman dari pelaku, dan adanya campur tangan keluarga dan budaya.[5]
Hal-hal ini membuat pelatihan terhadap tenaga kesehatan mengenai konsultasi KDRT dan KPI menjadi penting. Salah satu tujuan yang diharapkan adalah peran tenaga medis untuk dapat mengubah pola pikir dan perilaku pasien KDRT agar dapat berdiri melindungi dirinya sendiri.[5]
Penanganan Pelaku KDRT
Penyelesaian masalah KDRT maupun KPI tidak akan berhasil jika hanya menangani korban, tetapi perlu strategi yang tepat dalam menangani pelaku kekerasan. Terapi pelaku harus efektif untuk mencegah kekerasan berkelanjutan atau berulang, serta tidak memberikan rasa aman palsu kepada korban.[6]
Sayangnya, pelaku kekerasan yang bersifat dominan seringkali sangat minim mendapatkan efek baik dari terapi perilaku kognitif maupun terapi kelompok yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman baru dengan program kesehatan mental yang kompleks dan individual, termasuk penegakan hukum yang dini. [6]
Secara khusus, harus dipahami beberapa faktor risiko pelaku kekerasan, yaitu faktor demografis, tipologi pelaku, kesiapan dan motivasi pelaku untuk berubah, serta kejadian pencetus seperti penggunaan zat dan masalah kesehatan mental. [6]
Kesimpulan
Isu kekerasan pasangan intim (KPI) di Indonesia masih belum banyak mendapat sorotan. KPI merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang cenderung meningkat selama pandemi COVID-19 sebagai efek samping dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain cedera akut, pasien kekerasan dapat memiliki efek kesehatan jangka panjang.[5]
Tenaga kesehatan sebagai tempat mencari pertolongan umumnya belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi pasien KDRT. Pelatihan tentang KDRT dalam bentuk skenario klinis bagi tenaga kesehatan di Indonesia dapat menjadi salah satu upaya. Selain itu, pedoman terapi untuk pelaku kekerasan memerlukan program kesehatan mental yang kompleks dan individual, seringkali dengan penegakan hukum yang dini.
Sangat diperlukan penelitian untuk menstandarisasi panduan pelatihan KDRT dan KPI tersebut sebelum akhirnya diterapkan di Indonesia. Sehingga sesuai dengan kondisi kebudayaan Indonesia dan dapat diaplikasikan oleh tenaga kesehatan, baik di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan.